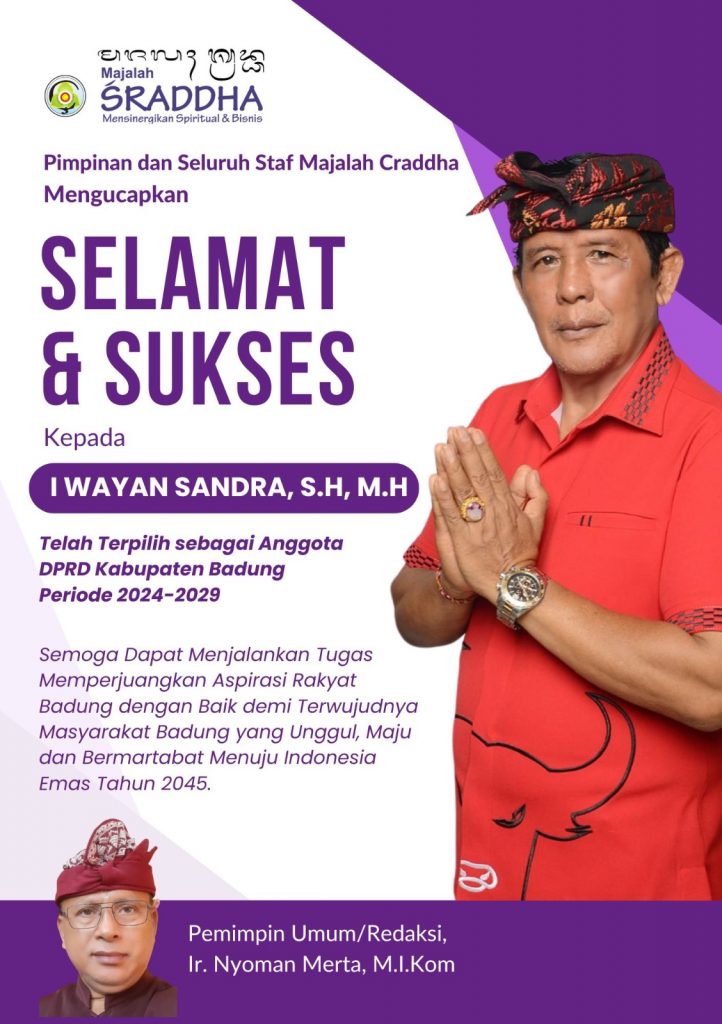Oleh : Wayan Windia *)
Saya agak skeptis ketika Presiden Jokowi menerima penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI), Los Banos, Filipina. Penghargaan itu berkait dengan swasembada beras. “Apa iya seperti itu” demikian rasa penasaran dalam benak saya. Rasa penasaran saya betul-betul terbukti. Beberapa bulan setelah Jokowi menerima penghargaan itu, Indonesia malah menerima fakta bahwa kita harus impor beras. Ya….baru saja kita impor beras sebanyak 500.000 ton, nilanya tak tanggung-tanggung, Rp. 4,4 Triliun. Kedatangan beras itu di pelabuhan, kabarnya “disambut” oleh Menteri Perdagangan, seperti kita kedatangan tamu agung.
Apa arti fakta ini ? Ini bukti bahwa betapa urgensinya beras bagi penduduk Indonesia. Khabarnya, kita harus menelusuri keberadaan beras hingga ke India. Beras yang tersedia di pasar dunia, banyak yang pecah-pecah alias remuk. Ini berarti, beras di pasar dunia sudah semakin langka. Meski kita punya uang, kalau beras langka di pasaran, lalu kita mau apa? Maka itulah, kita jangan seenaknya menghancurkan sawah untuk jalan toll, atau infrastruktur lainnya. Justru mesti sebaliknya, sawah harusnya dimuliakan (Swi Kerthi).
Kenapa saya skeptis? Karena saya curiga, dari mana datangnya beras yang swasembada itu? Logikanya adalah bahwa beras itu datangnya dari sawah Indonesia. Tapi, kalau sawahnya sudah hancur-lebur dihantam infrastruktur, lalu tanaman padi yang menghasilkan beras, tumbuhnya di mana? Kolega saya di Bappenas memberi info bahwa sawah di Bali pada 2019, sudah minus 10.000 hektar, untuk bisa memenuhi ketahanan pangan penduduk Bali. Apalagi di Jawa, pastilah sawahnya lebih hancur-lebur. Padahal sumber beras di Indonesia sekitar 60% berasal dari Jawa dan Bali.
Jokowi sudah sejak lama berteriak tentang ancaman krisis energi dan pangan. Kemudian seolah-olah sangat gelisah melihat permasalahan pangan di Indonesia. Lalu membuat berbagai pernyataan agar aparatnya mengontrol arus pasokan pangan, dll. Kemudian Kapolri menyambut dengan memerintahkan aparatnya agar menindak tegas masyarakat yang melakukan manipulasi bahan pangan. Tetapi apa yang diucapkan Jokowi tidak sesuai dengan tindakannya. Yakni berbagai kebijakan yang menghantam banyak sawah untuk membangun berbagai infrastruktur. Lebih celaka lagi, kebijakan ini diikuti oleh pemerintah daerah seperti di Bali.
Hal itu persis seperti anekdutnya Gus Dur, yang menyentil salah satu karakter para pejabat Indonesia. Bahwa apa yang diucapkan, sering tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kiranya sudah jelas masalah pangan adalah permasalahan produksi, distribusi, dan keamanan pangan. Permasalahan produksi, hingga saat ini sumbernya adalah sawah. Belum ada teknologi yang secara masif mampu meningkatkan produksi rata-rata di atas 6,5 ton GKP per hektar. Kalau sawahnya terus-menerus dihancurkan, lalu dapat beras dari mana ?
Saya mempunyai seorang mahasiswa S1 yang menulis skripsi tentang dampak pembangunan jalan toll di sebuah kawasan di Jawa. Dampaknya sangat buruk bagi petani. Di samping itu, pihak investor membangun saluran irigasi bagi petani, yang semakin ke hilir semakin dangkal. Tentu saja petani yang berada di hilir tidak mendapatkan air yang cukup. Maka dapat diduga akhirnya, kawasan sawah milik petani di hilir, dicaplok lagi oleh kaum investor.
Demikianlah, karena Jokowi doyan infrastruktur, maka tentu saja akan diikuti oleh anak buahnya di daerah. Pemda Bali akhirnya juga memutuskan membangun infrastuktur jalan toll yang (menurut Walhi Bali), mengantam hampir 500 hektar sawah di sepanjang Gilimanuk-Mengwi. Pemda nyaris tidak peduli dengan keluhan masyarakat. Di Medsos, dan juga di kalangan warga kampus di Unud, cukup banyak yang mengeluh dan tidak setuju dengan pembangunan jalan toll itu. Bahkan beberapa di antara mereka mengeluh karena sawah leluhurnya ikut dihantam jalan toll. Namun, mereka rakyat kecil, tak memiliki power untuk membela diri. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.
Ulasan di atas menunjukkan, betapa pemerintah sangat kurang memperhatikan petani dan sektor pertanian di Bali dan Indonesia. Pemerintah hanya memperhatikan pihak konsumen dan ketakutan dengan inflasi. Lalu petani harus ditekan-tekan dan jadi korban. Menteri Pertanian sempat bersuara untuk membela petani. Agar masyarakat Indonesia harus rela untuk beberapa saat membeli harga beras petani dengan harga yang mahal. Dengan demikian petani akan bisa menikmati keuntungan yang sepadan dari hasil sawahnya. Dampaknya, petani akan senang bertani.

Tetapi suaranya yang memihak petani, nyaris lenyap terbawa angin. Ternyata pemerintah tetap saja bersiteguh impor beras guna membela konsumen. Friksi antara Bulog dan Kementan memang sudah lama terjadi. Bulog selalu inginnya impor beras, tetapi Kementan selalu berusaha untuk menahan-nahan. Kalau saja masyarakat (konsumen) bersiap untuk sedikit “menderita” dengan harga beras yang mahal dan inflasi yang agak tinggi, maka petani akan bergairah untuk bertani.
Kalau hal itu bisa terjadi, maka kemiskinan akan berkurang, ketimpangan pendapatan akan semakin berkurang, urbanisasi akan berkurang, pedesaan akan berkembang, dan ekonomi akan bertumbuh secara berkelanjutan (meski dengan level perlahan-lahan). Fakta yang terjadi justru sebaliknya, kalau pun ekonomi bertumbuh sangat cepat, namun tiba-tiba ambruk diterjang virus.
Masyarakat Indonesia inginnya serba instan, tergesa-gesa, dengan harapan kesejahteraan yang tidak proporsioanl. Apa-apa kok inginnya serba cepat. Agar cepat menjadi kaya, lalu korupsi. Agar cepat menjadi pejabat, lalu melakukan politik uang dalam pemilu dan pilkada. Agar cepat populer, petani harus ditekan-tekan. Generasi ini, tampaknya lupa bahwa kemerdekaan yang kini kita nikmati, harus direbut dengan sangat sabar dan dengan perjuangan yang sangat panjang. Taruhannya adalah keringat, air mata, bahkan tetesan-tetesan darah. Namun, itu seolah tak berarti sama sekali saat ini. Tak cukup hanya dengan merenung di setiap hari Pahlawan, mestinya dikasi bukti peduli petani dengan aksi. *) Penulis, adalah Guru Besar (Emeritus) pada Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar.