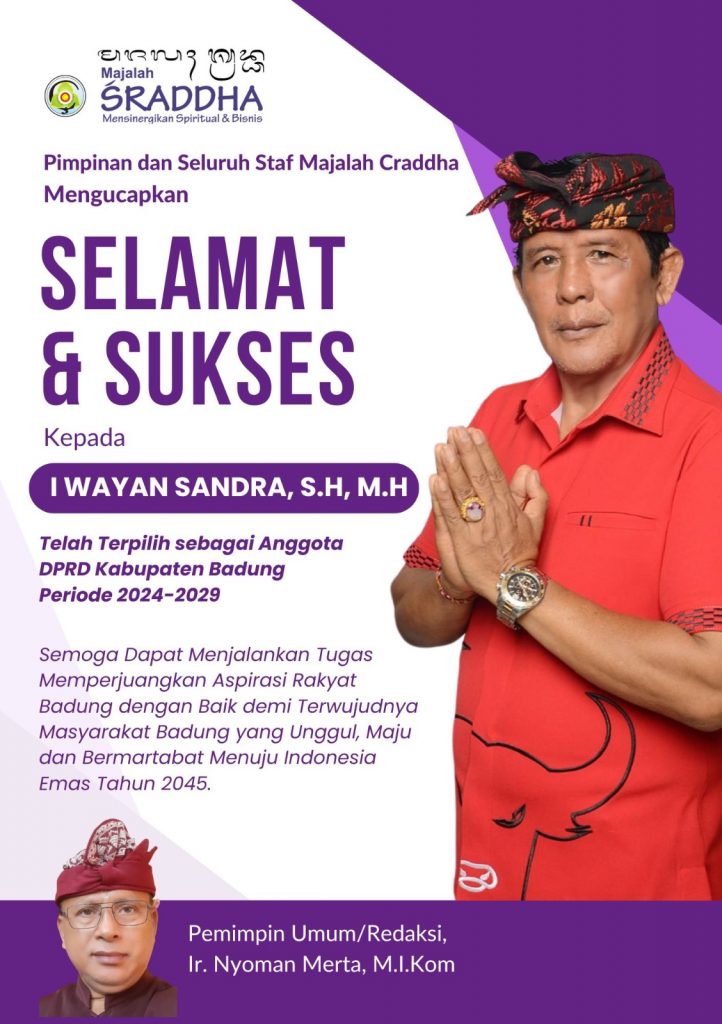Oleh : Wayan Windia
Gubernur Bali, Wayan Koster telah mengeluarkan pernyataan, bahwa Pulau Bali akan mulai dibuka untuk pariwisata domestik. Dinilai bahwa, keputusan itu diambil, sudah melalui berbagai tahapan. Tetapi berbagai elemen masyarakat menyatakan, bahwa keputusan gubernur itu, terlalu tergesa-gesa. Karena penyebaran virus Corona masih marak di Bali, di Indonesia, dan juga di dunia. Kritik diantaranya disampaikan oleh ekonom-spiritual Gde Sudibya. Ia ingin agar kesehatan masyarakat Bali harus menjadi acuan utama. Gde Sudibya pernah menjadi anggota MPR utusan daerah, dan menjadi anggota badan pekerja. Oleh karenanya, visi, renungan, dan pemikrannya perlu dihormati.
Dua kawasan pusat pariwisata di Bali yakni di Kota Denpasar dan di Kab. Badung, mengindikasikan bahwa serangan virus Corona masih terus menanjak. Sebagai pembanding, bahwa Vietnam baru memulai membuka transportasinya (pariwisatanya), setelah tidak ada lagi serangan Corona. Tetapi setelah 100 hari dibuka, langsung muncul lagi serangan Corona dari transmisi lokal. Ini berarti sangat riskan sekali membuka Bali, sebelum virus Corona tuntas dan vaksin Corona ditemukan.
Kalau pintu untuk pariwisata di Bali betul-betul dibuka, dan kemudian serangan virus Corona kembali melonjak, sungguh kasihan masyarakat Bali kita. Banyak masyarakat harus menjadi korban. Demikian juga para dokter dan perawat di rumah sakit. Tetapi, itulah biaya sosial (social cost) yang harus dibayar oleh masyarakat Bali, demi untuk kehidupan pariwisata. Apakah masyarakat Bali harus dikorbankan demi pariwisata? Jadi, slogan bahwa “Bali untuk pariwisata” betul juga adanya.
Kasus arus-balik setelah hari raya Idul Fitri, harus dianggap sebagai pelajaran. Begitu arus balik mulai ramai, maka mendadak sontak, serangan Corona berbasis transmisi lokal mulai terjadi di Bali. Sebelumnya, yakni sebelum Idul Fitri, serangan Corona di Bali masih terkendali. Hal ini membuktikan bahwa semakin banyak ada interkasi masyarakat, serangan Corona akan semakin menggila. Hal itu disebabkan karena masyarakat kita, masih dalam kondisi sangat tidak disiplin.
Sebelumnya, bertahun-tahun masyarakat Bali telah juga harus membayar biaya sosial lainnya. Di antaranya, harga-harga yang mahal, polusi, intrusi air laut, kemacetan lalu lintas, dan sawah-sawah yang terkonversi. Sekitar satu persen per tahun sawah-sawah di Bali hilang, sebagai implikasi dari pembangunan fasilitas parwisata.
Sekarang kita mengeluh bahwa harga hortikultura merosot tajam. Karena pariwisata macet total. Tetapi ketika sebelumnya, harga-harga hortikultura tinggi, petani di Bali tetap saja miskin. Indek Nilai Tukar Petani (NTP) tidak lebih dari 105. Hal itu disebabkan karena pihak hotel (kapitalis) membayar pembelian hortikultura kepada tengkulak, sekitar tiga bulan setelah proses pembelian. Maka tengkulak tentu saja harus menekan harga di tingkat petani. Jadi, petani yang sudah miskin harus memberi subsidi kepada tengkulak, dan pihak hotel. Sekali lagi, itulah biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat Bali untuk pariwisata.
Sementara itu, keuntungan dari pariwisata belum tentu beredar di Bali. Banyak di antaranya sudah lari ke luar Bali dan bahkan mungkin ke luar Indonesia. Tetapi apa mau dikata? Pariwisata dan kapitalisme sudah menggurita di Bali. Sudah tidak ada jalan lain, dan tidak ada jalan kembali. Kita harus segera melakukan moratorium terhadap sektor pariwisata Bali. Tetapi siapa yang berani?
Gubernur Koster sudah melihat dengan tajam fenomena ini. Lalu dikeluarkanlah Pergub No. 99 tahun 2018. Tujuannya agar pihak hotel dan lain-lain harus membayar kontan produk petani, dengan keuntungan 20% di atas biaya usaha tani. Tetapi nyatanya tidak jalan dengan maksimal. Apalagi saat ini, ketika ada serangan Corona pada sektor pariwisata. Ya pastilah, mana ada kapitalis yang bersedia dikurangi keuntungannya? Orientasi kapitalis hanyalah : keuntungan, produkivitas, dan efesiensi.
Itulah sebabnya, kenapa pernah ada wacana untuk memungut fee bagi wisatawan yang berwisata di Bali. Agar jelas, ada sumbangan riil dari wisatawan untuk Bali. Janganlah keuntungan dari kedatangan wisatawan, hanya dinikmati oleh pihak hotel atau kapitalis. Sedihnya, wacana ini pun akhirnya tenggelam entah ke mana. Lagi-lagi, kiranya hal itu disebabkan karena ada serangan dari kaum kapitalis, yang tidak mau keuntungannya berkurang. Mudah-mudahan Pemerinta Provinsi Bali mampu berdialog dengan Pemerintah Pusat dan stakeholders lainnya, untuk “memenangkan” pertarungan melawan kapitalis.
Saat ini, geliat ekonomi Indonesia sangat bergantung dari geliat pariwisata di Bali. Kalau Bali bersedia membuka pariwisatanya, maka lambat namun pasti, ekonomi Indonesia akan ikut menggeliat. Masalahnya adalah, apakah masyarakat Bali harus lagi-lagi dikorbankan, dan harus menanggung biaya sosial untuk mengusung pariwisata ? Kesehatan masyarakat Bali terlalu mahal untuk dicoba-coba dan dipertaruhkan, hanya demi untuk kepentingan kapitalis.
Tetapi kita berada dalam rangkuman NKRI. Kita harus taat kepada pemerintah pusat. Apalagi pihak Pusat dan Bali berada dalam satu jalur politik. Saya kira negosiasi yang terjadi, akan mengalir pada “kekalahan” di Pemerintah Bali. Namun, kita memerlukan kemampuan lobi pimpinan daerah di Bali, untuk berdebat, sejauh mana keamanan dan kesejahteraan masyarakat Bali bisa dijamin.
Saya berpendapat bahwa, daerah yang dibuka untuk pariwisata, haruslah kawasan yang sudah mulai “bebas” dari serangan Corona. Kalau NTT memang sudah memungkinkan untuk itu, sebaiknya NTT yang dibuka terlebih dahulu. Di NTT, ada Labuhan Bajo, Pulau Komodo, kawasan Pulau Sumba dll. Saya kira keindahan dan ke-khas-an kawasan Pulau Flores, tidak kalah hebat dengan Pulau Bali.
Sejak beberapa waktu yang lalu, sejumlah wisatawan sudah mulai mengalir ke NTT. Jokowi juga sudah berjanji akan mengembangkan Labuhan Bajo secara maksimal. Maka kinilah saatnya untuk membuka kawasan itu secara lebar bagi pariwisata. Pembangunan jangan hanya terlalu Bali dan Jawa sentris. Hal ini juga sangat berbahaya secara politis. Kita sudah ada pengalaman yang pahit pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai pemberontakan dan sparatisme muncul karena pembangunan Indonesia yang dianggap tidak merata. Pada saat itu, pembangunan Indonesia dianggap terlalu Jawa sentris. *) Penulis, adalah dosen pada Fak. Pertanian Univ. Udayana, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra, Sukawati, Gianyar.